Sapaan "Teteh" itu masih terngiang asing di telinga. Seorang ibu menyapaku dengan ramah, mencampurkan kata itu dalam ocehan panjangnya. Aku cuma bisa balas senyum, mengangguk. Jujur saja, waktu itu aku belum paham betul arti setiap ucapannya. Bukan ogah menjawab, tapi perbedaan bahasa memaksaku untuk mencerna lebih pelan. Semua ini kurasakan begitu pertama kali kaki ini menapak dan menetap di Desa Cintaratu, Pangandaran.
Baru beberapa hari sebelumnya aku masih di Jatinangor. Jadi, sapaan-sapaan baru seperti "Teteh" untuk perempuan atau "Akang" untuk lelaki, dengan intonasi Sunda yang khas lembut itu, masih terasa ganjil. Kuping belum biasa. Lidah pun serba canggung, gugup, takut salah tangkap. Tapi di tengah kebingunganku itu, justru warga setempat yang jadi penyemangat.
Ada seorang ibu yang akhirnya akrab denganku. Dialah yang pertama kali menunjukkan kehangatan itu.
"Mau kemana, Teteh? Dari tadi lihatnya sibuk sekali," katanya suatu sore.
Saat aku bingung, cuma bisa senyum atau tatap kosong, ia malah tertawa kecil. Tak tersinggung sedikitpun. Malah kemudian ia menawarkan makanan, bantuan, dengan keramahan yang tulus. Seolah-olah bahasa tak lagi jadi tembok tebal yang memisahkan kita.
Pengalaman serupa berulang dari warga lain. Hampir tiap hari, setiap lewat depan rumah, selalu ada senyum, sapaan, atau sekadar anggukan. Gestur kecil itu yang bikin hati merasa diterima. Perlahan aku sadar, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perbedaan bahasa: rasa kemanusiaan yang hangat.
Bantuan datang dalam bentuk yang tak terduga. Kadang ada yang tiba-tiba menghampiri dan nawarin tumpangan. Lain waktu, ada yang sekadar nanya kabar, memastikan aku baik-baik saja di tempat baru. Aku sempat merasa malu dan sungkan, sih. Tapi di sisi lain, terharu juga. Ternyata kepedulian nggak selalu lahir dari latar belakang yang sama. Ia bisa muncul dari ketulusan biasa, dari perhatian yang sederhana.
Semakin hari, semua jadi semakin nyata. Kedekatan itu tumbuh dari interaksi-interaksi kecil yang terus berulang. Aku belajar satu hal: kedekatan dan rasa kekeluargaan nggak akan pernah bisa dihalangi oleh perbedaan bahasa. Justru, dari situlah kedekatan itu dibangun. Dari usaha saling membuka, saling memahami.
Senyum, sapaan, tegur sapa itu adalah bahasa universal yang mampu memecah sekat perbedaan. Di Pangandaran, aku mungkin belum mengerti setiap kata dalam bahasa Sunda. Tapi aku sekarang tahu, ketulusan punya caranya sendiri untuk bisa dimengerti oleh siapa saja.

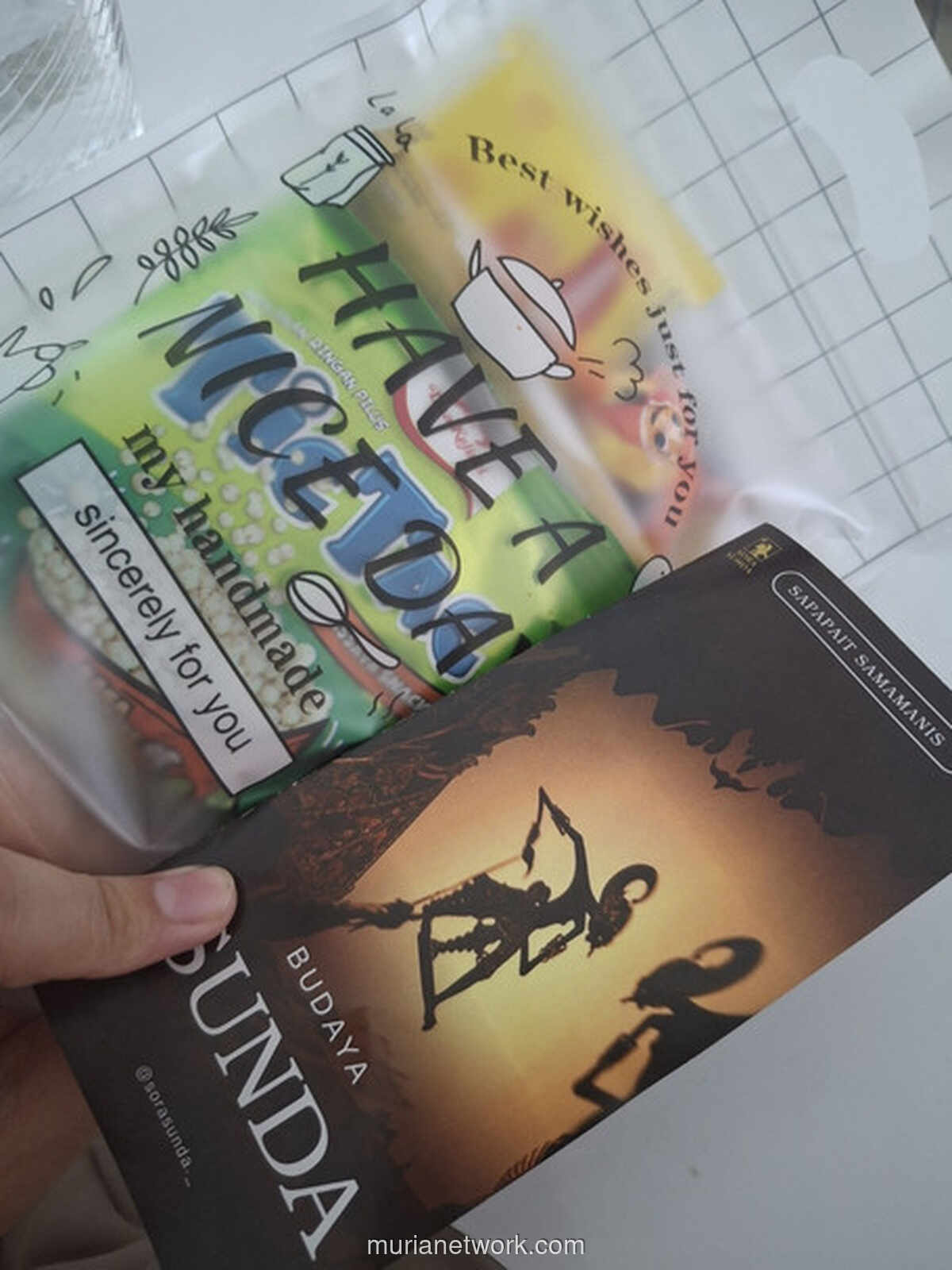









Artikel Terkait
Studi Buktikan AI Tingkatkan Akurasi Diagnosis Dokter di Rwanda dan Pakistan
Harga Cabai Rawit di Maros Tembus Rp55 Ribu per Kg Jelang Ramadan
SIM Keliling Polrestabes Bandung Buka di Dua Lokasi Rabu Ini
Benjamin Sesko Selamatkan MU dari Kekalahan dengan Gol Injury Time Lawan West Ham