Aksi Iklim: Bukan Cuma Soal Teknis, Tapi Soal Hati Nurani
Oleh: Saleh Hidayat
Anggota "Diskusi Reboan" yang difasilitasi Indonesian Democracy Monitoring (InDemo), Jakarta
Bayangkan ini: November 2025 di Belém, Brasil. Suasana COP30 ternyata tak seperti konferensi iklim biasanya. Ada sesuatu yang berbeda. Lewat inisiatif baru bernama Global Ethical Stocktake (GES), percakapan soal iklim bergeser drastis. Tak lagi didominasi bahasa teknis yang dingin, tapi mulai menyentuh ranah moral dan etika. Intinya, melawan perubahan iklim kini dipandang sebagai kewajiban moral seluruh umat manusia, bukan sekadar kepatuhan pada aturan internasional.
Di sisi lain, ada Belém Political Package yang jadi buah bibir. Ini paket keputusan politik utama hasil COP30, mencakup empat isu besar mitigasi, adaptasi, keuangan iklim, plus kerugian dan kerusakan. Teks drafnya sendiri sudah beredar sejak 18 November 2025.
Yang menarik, GES menawarkan kerangka evaluasi baru untuk NDC (Nationally Determined Contributions) edisi 2025. Jadi, komitmen iklim suatu negara tak lagi dinilai semata dari angka penurunan emisi. Tapi juga dari kualitas etisnya: sejauh mana melibatkan kelompok marjinal, menjamin keadilan untuk anak cucu, dan transparan dalam pembagian manfaat.
Kilas Balik Paris, dan Efek 'Ratchet' yang Mengunci
Perjanjian Paris 2015 memang jadi momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, hampir seluruh negara di dunia sepakat membatasi kenaikan suhu global jauh di bawah 2°C, dan berusaha mengejar batas 1,5°C. Yang tak kalah penting, ada efek 'ratchet' di sini. Setelah diratifikasi secara masif, target iklim sebuah negara tak boleh diturunkan. Hanya bisa ditingkatkan.
Namun begitu, perjalanan tak selalu mulus. Pandemi COVID-19 sempat mengganggu momentum. Tapi di balik itu, justru membuka peluang. Banyak paket stimulus pemulihan bernilai triliunan dolar dialirkan ke investasi hijau. Sebuah studi di jurnal Nature bahkan membuktikan, investasi semacam ini punya dampak ekonomi yang lebih besar ketimbang menanam modal di sektor fosil.
Jadi, transisi energi bukan cuma soal moral. Tapi juga pilihan yang rasional secara ekonomi.
Hambatan Nyata Menuju 2030
Laporan IPCC AR6 (2022) tegas: emisi global harus turun 45% pada 2030 dibanding level 2010 agar target 1,5°C masih mungkin. Tapi, jalan menuju sana terhalang tiga kendala besar.
Pertama, ketergantungan pada energi fosil terutama batubara di Asia Tenggara dan Selatan. Kedua, pendanaan iklim yang masih jomplang. Negara maju belum sepenuhnya memenuhi janji mereka. Ketiga, tata kelola partisipatif yang lemah. Pengetahuan lokal dan suara masyarakat adat sering diabaikan saat merumuskan kebijakan iklim.
Di Indonesia, masalahnya makin kompleks. Deforestasi untuk komoditas, ketergantungan pada batubara yang masih di atas 60%, dan minimnya peran masyarakat adat dalam program FOLU Net Sink 2030 adalah contoh nyata. Padahal, program yang menargetkan sektor kehutanan dan lahan sebagai penyerap karbon bersih itu sangat bergantung pada peran masyarakat adat sebagai penjaga hutan.
Tanpa mereka, target ambisius itu bisa jadi sekadar angka di atas kertas.


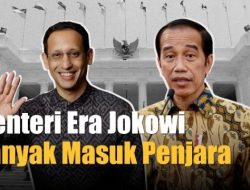

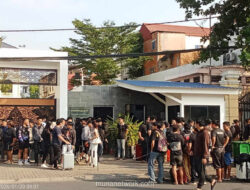






Artikel Terkait
Mentan Ancam Alihkan Anggaran Daerah yang Tak Serius Cetak Sawah
Komnas HAM Tegaskan Kritik Kebijakan Pemerintah Adalah Hak yang Harus Dijamin
Laporan Ungkap Aliran Dana Terduga Teroris Lewat Binance, Pegawai Penyelidik Malah Diberhentikan
Tren Bukber Ramadan di Makassar Beralih ke Restoran dengan Konsep Estetik