Kalau dirunut, korupsi punya silsilah yang panjang. Bukan anak haram zaman reformasi. Ia sudah matang sejak era kolonial. Ambil contoh VOC, raksasa dagang itu. Runtuhnya bukan cuma karena serangan musuh, tapi lebih karena kebusukan dari dalam. Pegawai yang mencuri, pejabat yang jual wewenang. Ada relasi telanjang antara penguasa kolonial, bangsawan lokal, dan para perantara. Dari sana kita mewarisi pelajaran pahit: korupsi bukan cuma soal mengambil uang. Ini soal membangun sistem saling menyandera.
Warisan itu dilanjutkan oleh rezim-rezim setelahnya. Sistem Belanda diadopsi, tapi bukan untuk keadilan. Untuk kontrol. Pelaku korupsi yang ketahuan dibiarkan, bahkan dipelihara. Dosa dijadikan arsip. Kesalahan jadi alat tawar. Kekuasaan berdiri bukan di atas kepercayaan publik, melainkan di atas ketakutan kolektif. Negara berubah jadi ruang gelap penuh rahasia, tempat semua orang pura-pura tidak tahu.
Di sektor swasta, wajahnya lebih halus. Korupsi tak selalu berupa amplop. Ia menyamar sebagai diskon khusus, bagi-bagi rejeki, atau sebut saja "uang rokok". Bahasanya dibuat lunak agar nurani tak berteriak. Pasar dan birokrasi bertemu dalam senyap, saling mengangguk. Kewirausahaan yang mestinya tentang inovasi, malah terjerat jejaring balas jasa. Ekonomi mungkin tumbuh, tapi etika mengerdil di sudut.
Namun begitu, di tengah badai, selalu ada segelintir orang yang sadar. Mereka berteriak di pantai saat ombak menggila. Suaranya kerap hilang dilumat angin. Tak ada patung untuk mereka. Mereka sering dicibir, dianggap naif, atau malah disingkirkan. Tapi merekalah penanda bahwa akal sehat belum sepenuhnya mati. Mereka paham: jika semua dianggap wajar, maka kejahatan akan berubah menjadi norma.
Barangkali benar ramalan suram itu negeri ini menuju bubar di tahun 2030. Bubar bukan karena perang, tapi karena kelelahan moral. Karena kita terlalu lama berdamai dengan yang busuk. Karena terlalu sering menyebut kejahatan sebagai kelaziman.
Jika itu benar terjadi, jangan salahkan sejarah. Sejarah hanya mencatat. Kitalah, hari ini, yang memilih: terus hanyut, atau berani berenang melawan arus. Meski sendirian.







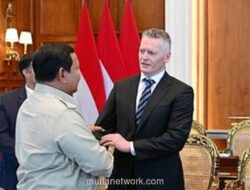



Artikel Terkait
Bare Metal Server: Fondasi Tepat untuk SaaS dan Startup yang Sedang Berkembang
Dua Mahkota Longsor di Gunung Burangrang Picu Bencana Dahsyat
Unit Pencegahan Gaza Gempur Geng Kolaborator, Sita Senjata Zionis
Said Didu Ungkap Isi 4 Jam Dialog Rahasia dengan Prabowo