Peradaban, Adab, dan Godaan Prinsip Absolut
Oleh: Radhar Tribaskoro
Buku terbaru Adhie M. Massardi, Peradaban Bukan Sekadar Civilization, lahir dari sebuah kegelisahan yang terasa begitu nyata. Sosok penulisnya sendiri cukup unik di tengah lanskap intelektual kita sekarang. Dia seorang pujangga yang tak larut dalam kemewahan istana, tapi juga tak sungkan menjadikan pinggir jalan sebagai ruang protes. Tulisannya baik puisi maupun esai selalu dibalut empati yang jernih, tanpa kehilangan ketajaman analisisnya.
Namun begitu, Mas Adhie saya biasa memanggilnya begitu bukanlah orang asing bagi kekuasaan. Dia politikus profesional, pernah menjabat Juru Bicara Presiden Keempat RI, Abdurrahman Wahid. Pengalaman dari dalam itulah yang membuatnya paham betul. Seringkali, bahasa moral yang luhur kalah telak oleh bahasa kepentingan yang pragmatis. Nilai-nilai mulia bisa dengan mudah larut jadi sekadar slogan saat berhadapan dengan mesin kekuasaan.
Buku ini, menurut saya, adalah puncak perenungannya. Ini bukan memoar politik, apalagi pamflet perlawanan. Ia menulis dengan jarak yang sudah terbentuk jarak dari kekuasaan, dari euforia reformasi, juga dari ilusi bahwa kemajuan selalu identik dengan keberadaban. Dunia modern ia amati dengan mata yang letih tapi jujur. Teknologi melesat, hukum berlapis, indeks kesejahteraan dipamerkan, tapi arah moral justru makin kabur.
Di sinilah paradoksnya muncul. Di tengah dunia yang mengklaim diri makin civilized, kekerasan justru dilembagakan secara sah. Ketidakadilan dihalalkan lewat prosedur yang rumit. Kehancuran ekologi dibungkus dengan bahasa rasionalitas yang dingin. Peradaban modern ibarat bangunan megah yang fondasi batinnya keropos. Dari kegelisahan inilah buku Adhie bermula.
Ia mempertanyakan istilah civilization yang selama ini dianggap sebagai ukuran final. Baginya, kemajuan material tak otomatis mencerminkan kematangan etis. Ada sesuatu yang lebih purba dan lebih menentukan daripada sekadar institusi atau teknologi: adab. Yaitu kesadaran tentang batas, tentang posisi manusia di hadapan sesama, alam, dan sesuatu yang melampauinya.
Dari titik tolak itulah buku ini bergerak. Bukan sebagai nostalgia religius, bukan pula penolakan terhadap modernitas. Ini lebih pada gugatan sunyi terhadap dunia yang terlampau percaya pada sistem, tapi ragu-ragu pada manusia.
Justru di sini percakapan penting dimulai. Ketika kritik terhadap modernitas teknokratis mengeras, muncul pertanyaan yang tak terhindarkan: sejauh mana adab bisa jadi fondasi bersama? Kapan ia berubah menjadi klaim kebenaran baru yang tak terbantahkan?
Pertanyaan itulah yang membuat buku ini layak dibaca dan juga layak dikritik.
Kritik Adhie tepat sasaran. Civilization sering dijadikan tolok ukur, seolah kemajuan material identik dengan kemajuan moral. Padahal sejarah membuktikan hal sebaliknya. Atas nama peradaban, kolonialisme berjalan, kekerasan dilembagakan, alam dieksploitasi habis-habisan. Dalam hal ini, civilization lebih sering jadi bahasa kekuasaan ketimbang bahasa etika.
Keunggulan buku ini ada pada keberaniannya mengembalikan pusat peradaban kepada manusia sebagai makhluk etis. Manusia tak pernah sepenuhnya "muat" dalam sistem. Kita hidup dalam makna, nurani, dan tanggung jawab bukan cuma sebagai unit fungsional ekonomi atau teknologi. Saat manusia direduksi jadi objek, hukum bisa berjalan tanpa keadilan, teknologi berkembang tanpa tanggung jawab. Ini bukan krisis administratif. Ini krisis makna.
Tapi di puncak argumennya yang reflektif, buku ini menghadapi godaan besar: godaan prinsip absolut.
Adhie menempatkan adab sebagai inti ontologis peradaban sebuah konsep yang kaya dan penting. Sampai di sini, argumennya kuat. Masalah muncul ketika adab kemudian ditambatkan secara hierarkis pada satu klaim: bahwa monoteisme adalah puncak kesadaran peradaban, karena hanya ia yang bisa menopang moral absolut.
Di sinilah terjadi lompatan normatif.
Pertanyaannya, benarkah prinsip moral universal hanya mungkin lahir dari monoteisme? Sejarah pemikiran manusia menunjukkan jawaban yang lebih kompleks. Tradisi Konfusianisme, Buddhisme, Stoisisme, bahkan humanisme sekuler, telah lama melahirkan prinsip martabat manusia dan tanggung jawab moral tanpa merujuk pada Tuhan yang personal. Etika tak selalu tumbuh dari absolutisme teologis. Seringkali ia lahir dari pengalaman penderitaan dan refleksi atas keterbatasan manusia.
Sejarah juga memperlihatkan sisi gelap klaim absolut. Atas nama Tuhan yang satu, perang suci dilancarkan, perbedaan dimatikan. Artinya, masalah utamanya bukan pada ada atau tidaknya prinsip absolut, tapi pada siapa yang menafsirkan dan bagaimana ia digunakan dalam struktur kekuasaan.
Di titik ini, buku ini justru berisiko mengulangi apa yang ia kritik: mengganti satu bahasa dominasi dengan bahasa dominasi lain dari civilization menjadi prinsip absolut.
Padahal, konsep adab sendiri menawarkan jalan yang lebih subur. Jika dipahami sebagai kesadaran akan batas dan kerendahan hati, ia tak memerlukan klaim sebagai puncak sejarah. Adab justru tumbuh dalam pengakuan bahwa manusia tak pernah memegang kebenaran secara utuh. Ia lebih dekat pada etika pembatasan diri daripada legitimasi kebenaran final.
Hal serupa terlihat dalam pembahasan HAM dan Palestina. Kritik Adhie bahwa HAM kehilangan jiwa saat digunakan secara selektif itu tepat. Palestina memang cermin telanjang peradaban modern: nilai universal dikhotbahkan, tapi ditangguhkan demi kepentingan geopolitik. Namun kegagalan HAM di sini bukan cuma soal hilangnya prinsip absolut. Ini juga soal arsitektur kekuasaan global yang timpang. Tanpa membaca dimensi struktural ini, adab berisiko jadi sekadar seruan moral yang menggugah, tapi tak cukup menggoyang sistem.
Begitu pula dengan analisisnya tentang teknologi. Diagnosanya tajam: manusia mengabdi dari tanggung jawab etis dan berlindung di balik "keputusan sistem". Tapi solusinya kembali normatif: kembalilah pada adab. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana adab bekerja di dunia algoritmik yang diatur korporasi dan pasar global? Tanpa desain institusional yang nyata, seruan etis bisa kalah oleh logika kekuasaan yang tak kenal ampun.
Pada akhirnya, Peradaban Bukan Civilization adalah buku yang penting. Bukan karena ia menawarkan jawaban final, tapi karena ia memaksa kita berhenti sejenak dari euforia sistem dan bertanya ulang tentang manusia. Kelemahannya justru terletak pada ambisinya sendiri: saat kritik terhadap absolutisme modern dijawab dengan absolutisme baru.
Mungkin peradaban yang beradab bukanlah yang menemukan prinsip paling absolut. Melainkan yang paling sadar akan keterbatasannya sendiri. Di sanalah adab menemukan makna terdalamnya: bukan sebagai puncak, tapi sebagai penjaga agar manusia tidak tergelincir oleh keyakinannya sendiri.
Cimahi, 6 Januari 2026

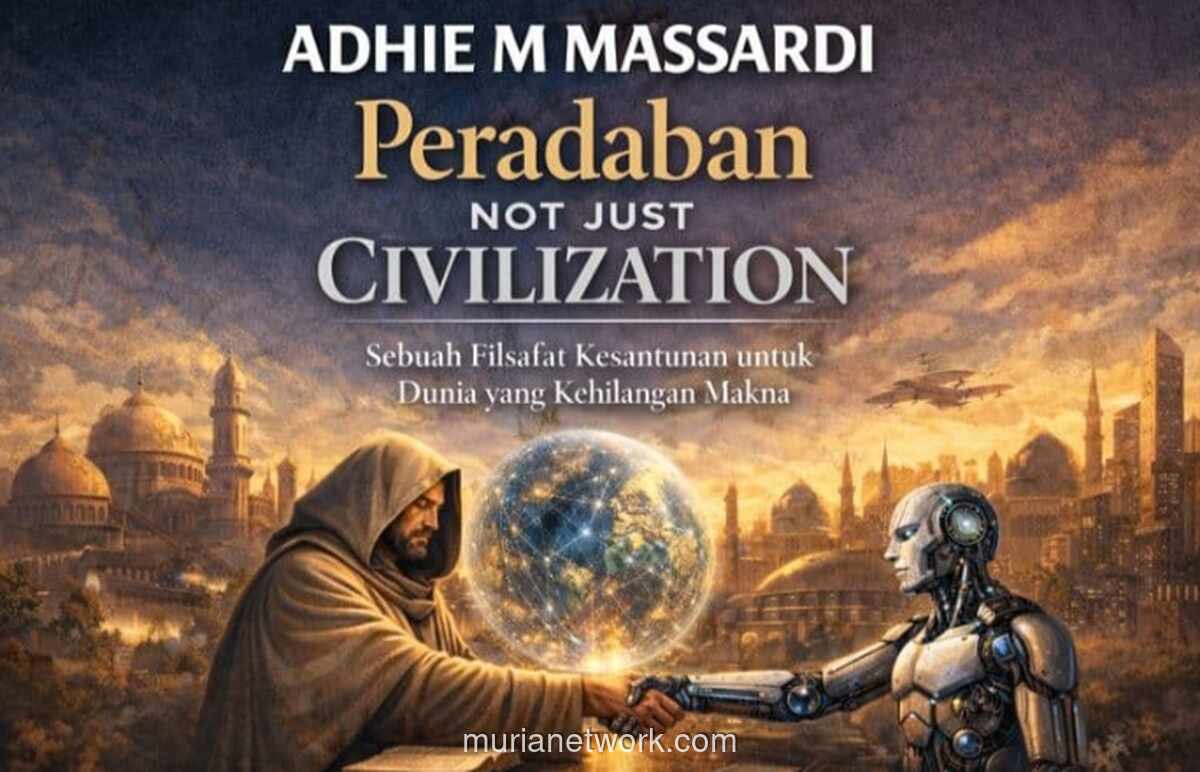









Artikel Terkait
AC Milan Tersungkur di San Siro, Kalah 0-1 dari Parma
Pakar Hukum Soroti Daya Paksa dan Krisis Kepercayaan Publik pada Aparat
Jadwal Imsak dan Subuh Medan 23 Februari 2026: Imsak Pukul 05.12 WIB
Imsak Yogyarta Pukul 04.16 WIB, Ulama Ingatkan Keberkahan Sahur dan Kuatkan Niat