Anak Muda di Persimpangan Masa Depan
Indonesia sedang berada di puncak bonus demografi. Jumlah anak muda yang masuk usia produktif jauh lebih besar. Secara teori, ini modal emas untuk mendorong negeri ini melesat. Tapi kenyataan di lapangan? Banyak yang justru gamang.
Lihat saja data terbaru. Dalam paparan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli belum lama ini, terungkap fakta yang cukup mencengangkan. Ternyata, lebih dari satu juta sarjana di negeri ini masih menganggur pada tahun 2025. Angka pastinya 1.010.652 orang.
Ini bukan cuma persoalan lulusan universitas. Angka pengangguran dari lulusan SMA dan SMK bahkan lebih besar lagi, masing-masing di atas dua juta dan satu setengah juta orang. Kalau dijumlahkan semua, total pengangguran kita mencapai 7,28 juta jiwa. Atau sekitar 4,76 persen dari angkatan kerja.
Memang, jumlah orang yang bekerja juga besar: 145,77 juta. Tapi persoalannya jadi rumit. Lapangan kerja formal tumbuhnya lambat. Sementara itu, sistem pendidikan kita seperti berjalan di tempat. Kampus dan sekolah masih berkutat pada teori, sementara industri membutuhkan keterampilan praktis dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Alhasil, banyak lulusan baru yang dianggap "belum siap". Mereka harus belajar lagi dari nol.
Akibatnya, banyak anak muda akhirnya terjun ke sektor informal atau gig economy. Pekerjaan seperti ini fleksibel sih. Tapi jangan tanya soal jaminan hari tua, perlindungan kesehatan, atau kepastian penghasilan bulan depan. Negara seolah bangga dengan semangat wirausaha dan kreativitas anak mudanya, tapi lupa membangun ekosistem yang aman dan layak untuk mereka.
Nah, di sinilah bahayanya. Bonus demografi bukan jaminan sukses. Kalau dibiarkan, ia bisa berbalik jadi beban sosial yang berat. Bayangkan saja, jutaan anak muda yang merasa tersisih, frustrasi karena pendidikan tinggi tak jua membawa pada pekerjaan yang layak. Ini bukan cuma soal ekonomi. Stabilitas sosial dan kepercayaan pada negara juga taruhannya. Ketika kerja keras dan ijazah tak lagi punya arti, yang retak adalah kontrak sosial kita semua.
Lalu, jalan keluarnya apa? Pelatihan singkat dan jargon 'ayo jadi entrepreneur' jelas tak cukup. Perlu langkah yang lebih serius dan terpadu.
Pertama-tama, reformasi pendidikan harus jadi prioritas. Kurikulum kita perlu disederhanakan dan dikaitkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Pendidikan vokasi dan politeknik harus ditingkatkan martabatnya, bukan dianggap sebagai pilihan kedua. Intinya, sekolah dan kampus harus jadi jembatan yang nyata menuju karir, bukan sekadar pabrik pencetak ijazah.
Kedua, kolaborasi dengan industri harus lebih dari sekadar tanda tangan di atas kertas. Perusahaan perlu dilibatkan sejak awal, dari menyusun kurikulum sampai menyediakan program magang yang bermakna. Pemerintah juga bisa memberi insentif bagi perusahaan yang mau merekrut dan melatih fresh graduate. Jangan terus menyalahkan anak muda "kurang pengalaman" kalau mereka tak pernah diberi kesempatan untuk mendapatkannya.
Ketiga, kita harus fokus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi itu bagus, tapi yang lebih penting adalah kualitas pekerjaan yang dihasilkan. Upah yang manusiawi, jam kerja wajar, dan jaminan sosial adalah hal mendasar. Sektor informal dan gig economy perlu diatur agar tak menjadi ladang eksploitasi baru.
Keempat, kebijakan ketenagakerjaan harus bisa melindungi pekerja muda. Fleksibilitas di era digital itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan rasa aman. Negara harus hadir untuk memastikan akses kesehatan dan perlindungan hukum bagi semua pekerja, di sektor manapun.
Kelima, dukungan untuk kewirausahaan harus realistis. Tidak semua anak muda cocok jadi pengusaha. Daripada memaksa, lebih baik sediakan akses modal, pendampingan, dan pasar yang jelas bagi mereka yang memang punya bakat dan minat. Jangan cuma berhenti di seminar motivasi.
Keenam, pemerataan pembangunan mutlak diperlukan. Selama kesempatan kerja hanya terkonsentrasi di kota-kota besar, anak muda dari daerah akan terus terpaksa urbanisasi. Investasi dan pusat ekonomi baru harus disebar untuk membuka peluang di berbagai wilayah.
Dan yang terakhir, yang paling krusial: libatkan anak muda dalam merancang kebijakan untuk mereka. Dengarkan suara dan pengalaman langsung mereka di lapangan. Kebijakan yang dibuat dari menara gading hanya akan gagal menyentuh akar persoalan.
Pada akhirnya, semua ini butuh keberanian politik. Hasilnya mungkin tidak instan dan penuh tantangan. Tapi masa depan bangsa ini sedang dipertaruhkan. Bonus demografi bukan sekadar angka statistik untuk dibanggakan dalam pidato. Ia adalah amanah.
Anak muda sebenarnya tidak menuntut banyak. Mereka hanya menginginkan kesempatan yang adil untuk bekerja keras, berkembang, dan hidup layak dari keringat mereka sendiri. Kalau negara bisa menyediakan itu, bonus demografi akan menjadi kekuatan dahsyat. Tapi kalau tidak? Kita semua akan menyaksikan sebuah peluang emas yang terbuang percuma.
Bagaimana menurut Anda?
(ed/jaksat-am)

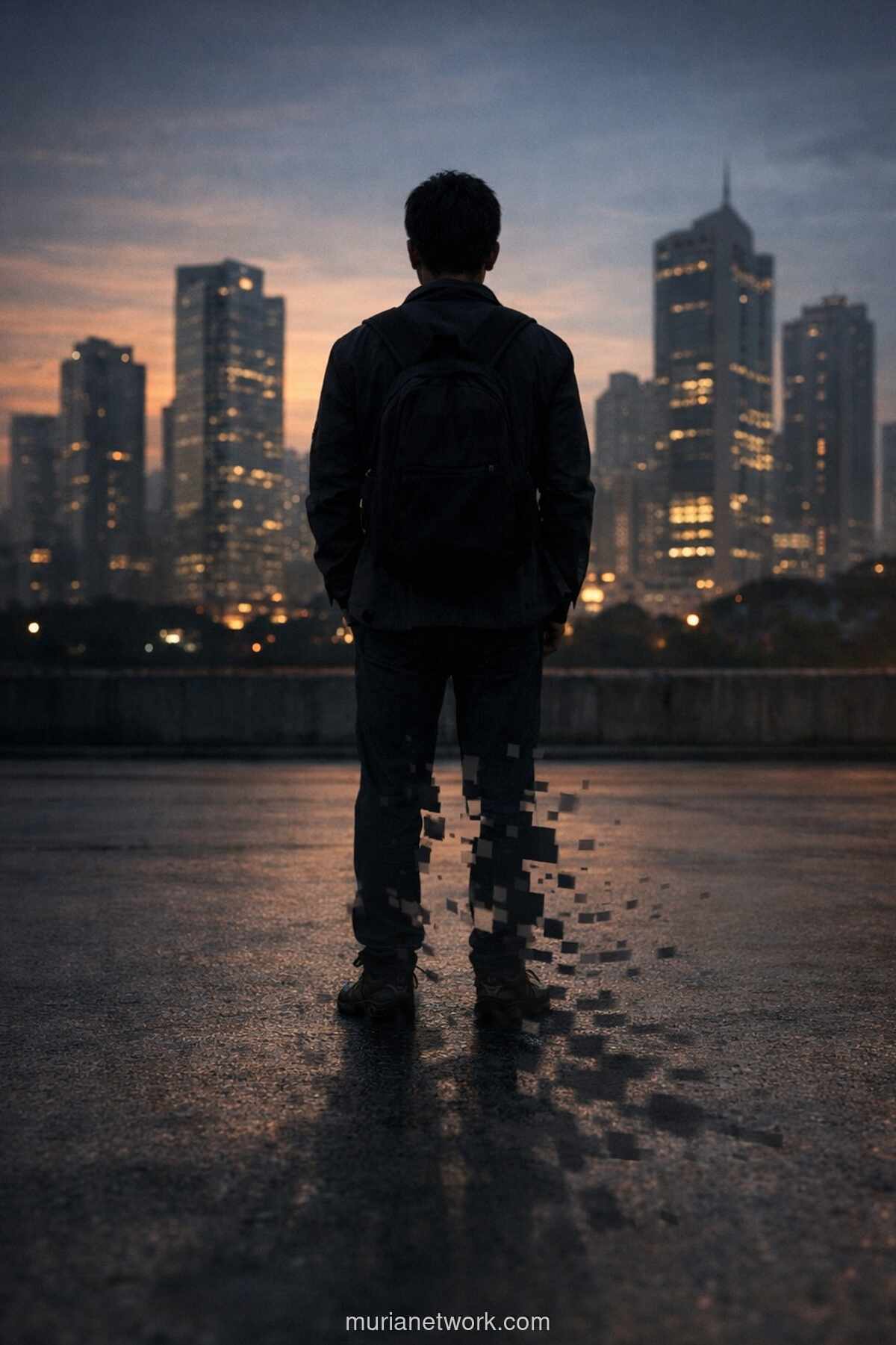








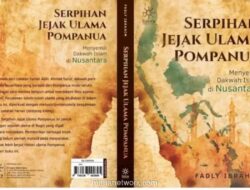
Artikel Terkait
Warisan Naskah dan Jejak Dakwah Syekh Abdul Majid di Pelosok Bone Terancam Rusak
Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas dalam Kecelakaan Maut di Tol Reformasi Makassar
Oknum Brimob Ditahan Usai Diduga Aniaya Siswa MTs Hingga Tewas di Tual
Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas dalam Kecelakaan Maut di Tol Makassar